Dalam beberapa hari terakhir, media internasional ramai memberitakan satu fakta yang mengejutkan banyak orang: Metropolitan Jakarta kini tercatat sebagai kota paling berpenduduk di dunia, menyalip Tokyo. Data ini bersumber dari laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Urbanization Prospects 2025, yang memperkirakan jumlah penduduk Jakarta mencapai hampir 42 juta jiwa pada 2025. Di bawahnya terdapat Dhaka dengan sekitar 37 juta jiwa dan Tokyo dengan sekitar 33 juta jiwa.
Bagi sebagian orang Indonesia, kabar ini mungkin menimbulkan rasa bangga. Namun bagi yang lain, justru memunculkan kekhawatiran. Jakarta sudah lama dikenal sebagai kota dengan persoalan kemacetan, banjir, polusi udara, permukiman kumuh, dan ketimpangan sosial yang tinggi. Menjadi “yang terbesar di dunia” lalu berarti apa?
Membaca berita tersebut, saya teringat pada sebuah buku klasik yang ditulis lebih dari 50 tahun lalu oleh E. F. Schumacher, berjudul Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered (1973). Buku ini sering dikutip sebagai kritik tajam terhadap obsesi dunia modern pada pertumbuhan dan skala besar. Schumacher mempertanyakan keyakinan bahwa “semakin besar, semakin baik” adalah prinsip universal yang selalu benar.
Namun, di sisi lain, dalam literatur ekonomi perkotaan modern terdapat buku yang hampir menjadi kebalikan pandangan tersebut, yaitu Edward Glaeser, Triumph of the City (2011). Glaeser justru berpendapat bahwa kota besar dan padat adalah masa depan peradaban manusia. Kota, menurutnya, membuat kita lebih produktif, lebih inovatif, dan dalam banyak hal justru lebih ramah lingkungan.
Pertanyaannya kemudian: jika Schumacher mengatakan kecil itu indah, apakah kota besar seperti Jakarta berarti tidak indah? Atau sebenarnya keduanya tidak benar-benar bertentangan?
Jakarta besar karena cara menghitungnya berubah
Sebelum menjawab pertanyaan normatif tersebut, penting untuk memahami satu hal mendasar: lonjakan peringkat Jakarta bukan karena pertumbuhan penduduk yang tiba-tiba, melainkan karena perubahan metodologi penghitungan kota oleh PBB.
Dalam World Urbanization Prospects 2025, PBB untuk pertama kalinya secara penuh menerapkan metode Degree of Urbanization, yaitu pendekatan berbasis data geospasial yang mengidentifikasi kota sebagai wilayah terbangun yang padat dan saling terhubung secara fungsional, bukan sekadar batas administratif. Dengan metode ini, kawasan suburban dan peri-urban yang secara ekonomi dan sosial terhubung dengan Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dihitung sebagai bagian dari kota.
Dalam laporan PBB disebutkan bahwa sekitar 30 juta penduduk Jakarta sebelumnya “tidak terlihat” dalam statistik resmi, karena tinggal di kawasan padat yang secara administratif berada di luar DKI Jakarta. Jadi, Jakarta tidak tiba-tiba tumbuh dua atau tiga kali lipat dalam beberapa tahun. Yang berubah adalah cara melihat dan mendefinisikan kota.
Pendekatan baru ini juga menunjukkan bahwa dunia sebenarnya lebih terurbanisasi daripada yang selama ini diperkirakan. Pada 2025, sekitar 45 persen penduduk dunia tinggal di kota, naik dari hanya 20 persen pada 1950. Dua pertiga pertumbuhan penduduk global hingga 2050 diproyeksikan terjadi di kawasan perkotaan. Kota besar seperti Jakarta adalah bagian dari tren global ini, bukan pengecualian.
Kekhawatiran Schumacher: ketika kota menjadi terlalu besar
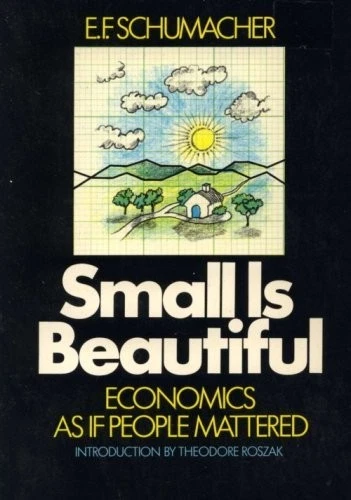
Schumacher menulis Small Is Beautiful pada masa ketika industrialisasi dan urbanisasi sedang meningkat pesat di banyak negara. Inti argumennya adalah sederhana: ekonomi hanyalah alat untuk kesejahteraan manusia, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Ketika sistem ekonomi mengejar pertumbuhan dan skala besar tanpa kendali, manusia dan lingkungan sering kali justru menjadi korban.
Dalam konteks kota, Schumacher cenderung skeptis terhadap megapolitan yang tumbuh tanpa perencanaan matang. Kota yang terlalu besar rawan menjadi tidak manusiawi: sulit dikelola, mahal infrastrukturnya, dan menciptakan jarak besar antara pengambil keputusan dan warga.
Jika dilihat dari kondisi Jakarta hari ini, kekhawatiran ini tampak relevan. Jakarta menghadapi beberapa masalah seperti:
- kemacetan kronis, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun;
- polusi udara, yang secara berkala menjadikan Jakarta salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia;
- permukiman kumuh, di mana jutaan orang tinggal dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka;
- ketimpangan ekonomi, dengan kontras tajam antara kawasan bisnis modern dan kampung padat di sekitarnya;
- krisis lingkungan, termasuk penurunan permukaan tanah hingga lebih dari 10 sentimeter per tahun di beberapa wilayah, serta ancaman banjir dan kenaikan muka laut.
Dalam situasi seperti ini, argumen Schumacher bahwa “besar” bisa menjadi masalah tampak tidak mengada-ada.
Argumen Glaeser: kota besar tetap menjadi magnet
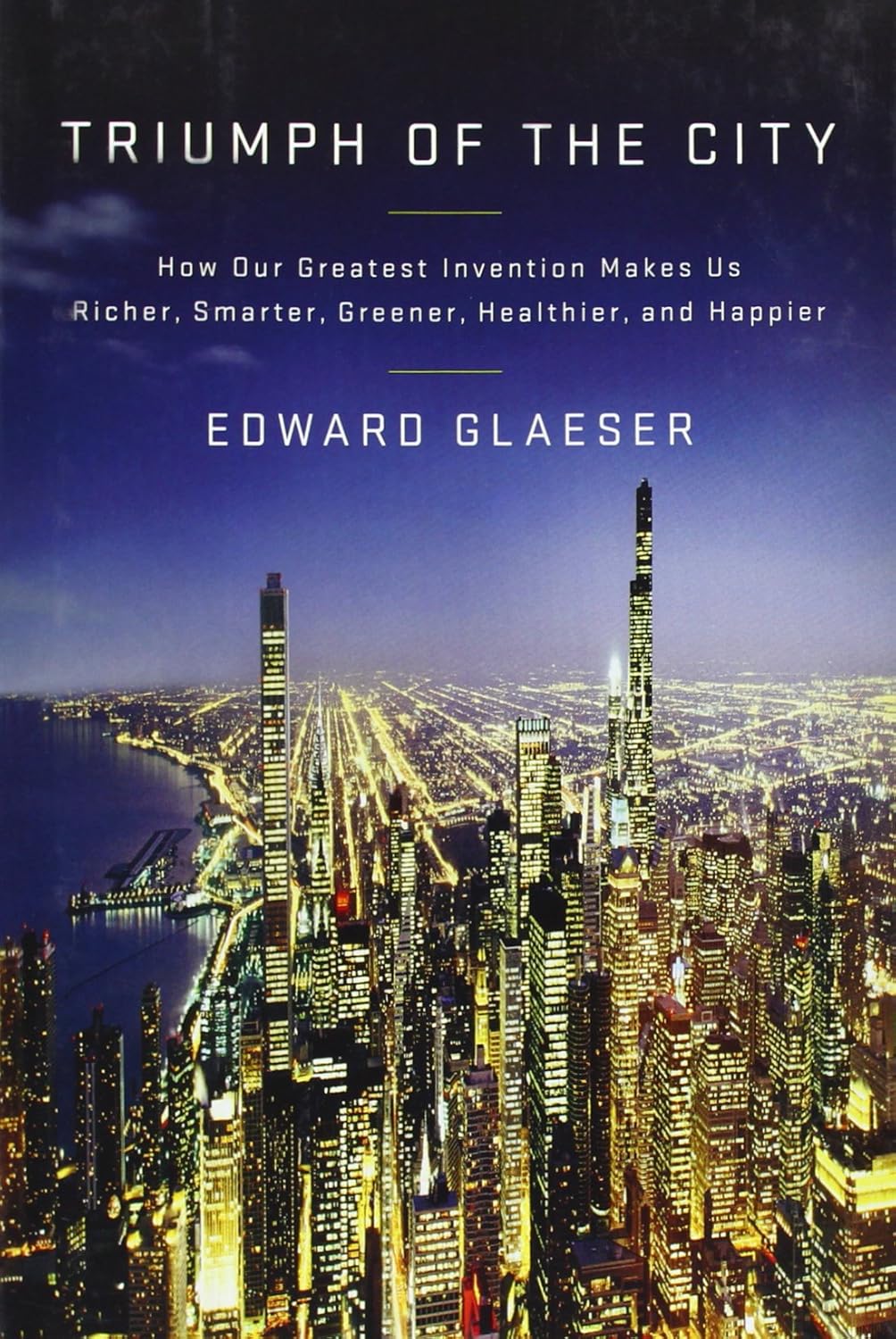
Namun Glaeser melihat kota dari sudut yang berbeda. Baginya, fakta bahwa orang terus berdatangan ke kota, meski macet, mahal, dan penuh tekanan, adalah bukti bahwa kota memberikan manfaat besar. Kota mempertemukan manusia, pengetahuan, dan peluang ekonomi dalam jarak yang dekat. Interaksi tatap muka yang intens mendorong inovasi, produktivitas, dan mobilitas sosial.
Glaeser juga menantang anggapan bahwa kota besar pasti tidak ramah lingkungan. Data menunjukkan bahwa emisi karbon per kapita penduduk kota padat sering kali lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah permukiman menyebar. Apartemen kecil, transportasi publik, dan jarak tempuh yang lebih pendek mengurangi konsumsi energi per orang.
Dari sudut pandang ini, Jakarta yang terus menarik migran desa-kota bukanlah anomali, melainkan refleksi dari logika ekonomi dasar: orang mencari kesempatan hidup yang lebih baik. Kota besar gagal bukan karena terlalu besar, melainkan karena tidak dikelola dengan baik.
Tidak benar-benar bertentangan
Walaupun sering diposisikan berlawanan, Schumacher dan Glaeser sebenarnya memiliki titik temu. Keduanya sepakat bahwa:
- Kota harus melayani manusia, bukan sebaliknya.
- Skala, besar atau kecil, bukan tujuan, melainkan konsekuensi.
- Tata kelola dan kebijakan menentukan apakah kota menjadi tempat hidup yang layak atau tidak.
Schumacher mengingatkan bahaya mengejar skala besar tanpa memperhatikan kualitas hidup. Glaeser mengingatkan bahwa menolak kota besar sama saja dengan menolak mesin kemajuan. Perbedaannya lebih pada penekanan, bukan pada tujuan akhir.
Dengan kata lain, perdebatan yang relevan bukan besar versus kecil, melainkan terkelola versus tidak terkelola.
Pelajaran dari kota di Eropa
Banyak kota di Eropa menunjukkan bahwa kepadatan tidak harus berarti kekacauan. Amsterdam, misalnya, adalah kota yang relatif padat dan kompak, tetapi memiliki kualitas hidup tinggi. Transportasi publik dan sepeda diutamakan, fungsi kota bercampur, dan ruang publik dirawat dengan baik.
Wina secara konsisten masuk peringkat kota paling layak huni di dunia, meskipun berpenduduk padat. Kuncinya adalah perumahan sosial skala besar, transportasi umum yang terintegrasi, dan perencanaan jangka panjang. Barcelona, meski menghadapi tantangan pariwisata massal, menunjukkan bagaimana desain kota kompak dengan ruang publik yang hidup dapat mendukung kehidupan urban.
Kota-kota ini tidak “kecil” dalam arti populasi, tetapi dikelola dalam skala yang manusiawi. Mereka mendukung argumen Glaeser tentang manfaat kepadatan, sekaligus mengafirmasi pesan Schumacher bahwa manusia harus menjadi pusat kebijakan.
Kota Amsterdam, Belanda
Kota Barcelona, Spanyol
Kota Wina, Austria
Jakarta dan pertanyaan ke depan
Status Jakarta sebagai kota terbesar dunia seharusnya tidak dipahami sebagai prestasi akhir, melainkan sebagai tantangan kebijakan. Dengan hampir 42 juta penduduk di wilayah metropolitan, persoalan perumahan, transportasi, lingkungan, dan ketimpangan tidak bisa ditangani secara parsial atau sektoral.
Pertanyaan pentingnya bukan apakah Jakarta terlalu besar, melainkan:
- apakah kota ini menyediakan pekerjaan yang layak;
- apakah transportasi publik cukup untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi;
- apakah kawasan kumuh ditangani sebagai bagian kota, bukan disingkirkan;
- apakah pertumbuhan kota selaras dengan daya dukung lingkungan.
Jika pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan kebijakan yang tepat, Jakarta yang besar tidak harus menjadi kota yang buruk. Ia bisa menjadi contoh bagaimana kota besar di negara berkembang dikelola secara lebih manusiawi.
Schumacher mengingatkan kita agar tidak silau oleh skala. Glaeser mengingatkan agar kita tidak takut pada kepadatan. Keduanya sepakat pada satu hal: kota adalah alat, bukan tujuan. Apakah kecil atau besar, kota hanya akan “indah” jika dikelola dengan baik dan berpihak pada penghuninya.
Dalam konteks Jakarta, menjadi kota terbesar dunia bukanlah akhir cerita. Justru di situlah cerita sesungguhnya dimulai.






















